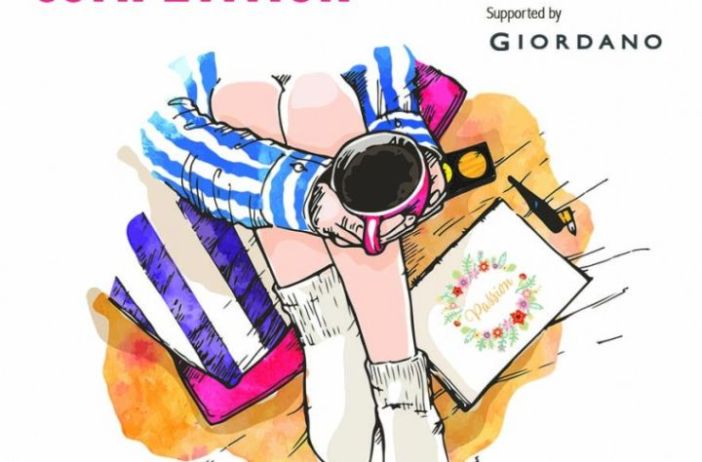Dalam enam minggu, ditemukan enam orang meninggal di Riverdise.
Korban pertama adalah seorang dokter perempuan, ditemukan tewas di bilik kamar mandi Rumah Sakit St. Eve. Wajahnya melepuh akibat cairan asam. Korban kedua adalah seorang anggota dewan, ditemukan dengan luka tembak di kepala pada saat resepsi pernikahan anak perempuannya di Gedung Zarachiel. Yang ketiga adalah seorang pedagang kembang di pasar. Ia ditemukan di dalam rumahnya sendiri di Raquel Street No. 21 yang luluh lantak oleh api. Seorang pengacara yang sedang menginap di Hotel Uriel dalam rangka bulan madu menjadi korban berikutnya. Istrinya yang menemukannya tewas di kamar mereka dengan lidah terpotong. Korban kelima ditemukan di taman kota. Wajah perempuan itu rusak dan di dadanya tergores luka materai. Belakangan diketahui, perempuan itu seorang PSK. Yang menjadi korban keenam adalah seorang remaja. Ia adalah anak laki-laki dari seorang pengusaha terkenal. Anak laki-laki itu ditemukan mati mengambang di Sungai Gabriel. Ia dicekik sebelum akhirnya dibuang ke sungai tersebut.
Riverdise adalah sebuah kota yang terkenal aman. Tingkat kejahatannya sangat kecil. Biasanya warga meninggal karena sakit, bukan karena dibunuh. Pihak kepolisian harus dipaksa bekerja semaksimal mungkin untuk mencari tahu penyebab kematian dan juga motif pembunuh. Namun mereka mengalami jalan buntu. Tidak ada jejak pelaku di setiap lokasi kejadian, bahkan tidak ada motif kuat siapa kira-kira yang mampu membunuh orang-orang ini. Apakah dilakukan oleh satu orang atau beberapa orang?
“Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kurang dari dua bulan, sudah enam warga kita yang meninggal.” Wajah Kepala Kepolisian Riverdise, Mr. Robertson, merah karena marah. Semua bawahannya hanya terdiam.
Mr. Robertson menarik napas panjang. Ia tahu ia tidak bisa menyalahkan anak buahnya. Mereka sudah bekerja keras. Namun nir hasil.
“Inspektur Boris.”
“Ya, Pak?”
“Cari laki-laki sok tahu itu dan mintalah dia untuk membantu penyelidikan kita. Paksa dia bagaimanapun caranya.”
“Baik, Pak.”
Di sebuah bar kecil di pinggir kota, seorang laki-laki dengan rambut berantakan duduk menikmati gelas wiski ketiganya. Tatapannya terpaku pada lampu neon yang membentuk nama bar. Dua buah lampu neon berkelap-kelip sebelum akhirnya padam. Mengubah nama bar menjadi Jim’s Butt. Pantat Jim. Padahal sebelumnya adalah Jim’s Butter.
“Kau masih pemabuk yang doyan minum wiski murahan rupanya,” kata Inspektur Boris yang sudah duduk di meja bar di samping laki-laki itu.
“Dan kau masih polisi menyebalkan yang akan datang ke sini hanya karena butuh sesuatu. Iya, kan?” Laki-laki itu meneguk habis minumannya dan menyodorkan kembali gelasnya ke bartender.
“Berikan dia minuman yang sedikit mahal dari itu,” kata Inspektur Boris menyela. “Dan satu untukku juga.”
“Kau sungguh murah hati sekali. Katakan apa maumu?”
“Kepala Kepolisian ingin kau membantu penyelidikan kami, Beltsazar.”
“Pasti kasus yang cukup berat sampai si tua bangka itu menyuruhmu mencariku.” Beltsazar meraih gelas minumnya yang sudah kembali penuh.
“Memangnya kau tidak mendengar tentang beberapa pembunuhan yang terjadi belakangan ini?” tanya Inspektur Boris heran.
Beltsazar hanya diam menikmati minumannya.
Inspektur Boris menggelengkan kepala. “Seharusnya aku tahu, kau juga pasti sudah menyelidiki semua kasus ini sendiri. Tipikal.”
“Traktir aku segelas lagi dan anggap saja aku mau membantu kalian.”
Inspektur Boris mengangkat tangannya memesan kembali minuman yang sama kepada bartender untuk Beltsazar.
Beltsazar meminta Inspektur Boris menemaninya pergi ke beberapa tempat hari itu juga. Mobil mereka berhenti di TKP pertama lalu ke TKP keenam yang lokasinya berdekatan. Beltsazar tak banyak melakukan apa-apa, ia hanya berkeliling TKP dengan mata seawas elang botak. TKP lainnya didatangi keesokan harinya.
“Kami menemukan beberapa petunjuk yang mungkin berkaitan. Ini tak pernah kami sebarkan ke media karena takut akan memengaruhi warga jika mereka tahu ada pembunuh berantai yang berkeliaran di kota ini.” Inspektur Boris mengeluarkan beberapa lembar foto dari sakunya. Ia memperlihatkan sebuah pola yang sama yang muncul di setiap TKP. “Bukankah itu terlihat seperti sebuah angka bagimu?”
Beltsazar mengamati sekilas foto-foto tersebut. Di dahi masing-masing korban ditemukan tulisan yang menyerupai 77’,7.
“Pihak kepolisian menyebutnya Pembunuh 777.”
“Kalau aku lebih memilih menyebutnya Peniru Malaikat yang Buruk.” Beltsazar menyalakan rokoknya yang tinggal sebatang yang baru saja diambilnya dari dalam saku.
“Peniru Malaikat?”
“Menurutmu, mengapa Lucifer memilih menjadi iblis?” Beltsazar berjalan meninggalkan TKP kelima.
“Apa hubungan Lucifer dengan kasus ini?” Inspektur Boris berusaha menyamai langkah Beltsazar.
“Jawab saja dulu.”
“Entahlah… karena dia ingin menjadi Tuhan mungkin?”
“Karena dia ingin diperhatikan. Sama seperti pelaku yang membunuh enam korbannya ini. Dia yang menyebut dirinya iblis. Tanda di dahi para korban itu bukan angka 7 melainkan bahasa Ibrani לילֵהֵ yang artinya Helel. Dia melakukan semua pembunuhan ini demi melengkapi semuanya menjadi satu bagian. Maksudku, tujuh.”
“Tujuh?”
“Akan ada tujuh pembunuhan. Tidakkah kau bisa menebak polanya?”
“Kalau aku sudah bisa menebak pola pelaku, aku tak akan bersusah payah meminta bantuanmu,” sungut Inspektur Boris.
“Baiklah,” kata Beltsazar sambil menarik napas panjang. “Pembunuhan pertama terjadi di Rumah Sakit St. Eve, yang kedua di Gedung Zarachiel, yang ketiga di jalan Raquel, keempat di Hotel Uriel, kelima di Taman Raphael, sedangkan korban keenam di Sungai Gabriel. Apa nama-nama lokasinya terdengar familier?”
“Ti-tidak.” Inspektur Boris menggeleng bingung.
“Itu semua adalah nama para malaikat. The Archangels.”
“The Archangels? Tapi Eve kan bukan malaikat.”
“Benar. Tapi malaikat yang digambarkan dekat dengan Eve adalah Samael. Samael diketahui sebagai suami dari Lilith, adik Eve. Samael dianggap satu dari tujuh malaikat utama walau pada akhirnya ia ikut membangkang bersama Lucifer.”
“Jadi pelaku terobsesi dengan malaikat?” tanya Inspektur Boris yang kini sudah membuka pintu mobilnya.
“Selain membunuh berdasarkan nama-nama malaikat, pelaku juga membunuh berdasarkan tujuh sakramen. Samael adalah sakramen urapan orang sakit, korban pertama adalah dokter yang dibunuh di rumah sakit dengan cairan asam. Zarachiel adalah sakramen perkawinan, korban kedua dibunuh saat berada di pesta pernikahan anaknya. Ia bahkan memegang buku doa karena Zarachiel dikenal sebagai pembawa doa. Korban ketiga ditemukan di Jalan Raquel. Korban ditemukan tewas terbakar karena Raquel adalah malaikat yang menghukum dengan api. Uriel adalah sakramen pengakuan dosa. Korban ditemukan tewas dengan lidah terpotong. Lalu korban kelima adalah seorang PSK yang ditemukan dengan wajah dan dada yang dimateraikan. Raphael adalah sakramen penabihsan. Korban keenam ditemukan tenggelam di sungai. Gabriel adalah sakramen baptisan.”
“Katamu akan ada tujuh korban.”
“Ya. Dan mungkin akan terjadi hari ini juga.”
“Hari ini?”
“Bukankah semua korban selisih jaraknya adalah enam hari. Hari ini adalah hari ketujuh sejak korban terakhir ditemukan.”
“Kau benar. Ini adalah harinya.” Inspektur Boris menepuk dahinya. “Sudah ada enam malaikat, tersisa satu malaikat lagi. Malaikat utama dari The Archangels adalah Michael, bukan?” Beltsazar mengiyakan.
“Jika pelaku membunuh sesuai lokasi yang memakai nama malaikat, maka yang terakhir ini akan ada di Gereja St. Michael. Benar kan? Aku harus segera melaporkan ini kepada Mr. Robertson.” Inspektur Boris segera melarikan mobilnya di jalanan.
“Ngomong-ngomong, sakramen apa yang akan dia gunakan?” tanya Inspektur Boris lagi.
“Perjamuan Ekaristi,” jawab Beltsazar dengan wajah lempengnya. Namun jika diperhatikan dengan saksama matanya berisi ketakutan.
“Perjamuan? Jangan-jangan…”
“Bom!” kata Beltsazar menjawab dugaan Inspektur Boris.
Tim penjinak bom dan pihak kepolisian Riverdise tiba di Gereja St. Michael saat sedang ada ibadah umum. Orang-orang yang ada di dalam dan sekitarnya diminta menjauhi area gereja sesuai dengan parameter yang sudah ditentukan. Sebuah bom aktif ditemukan di bawah mimbar. Tim penjinak bom berhasil mengamankannya. Kepolisian Riverdise mendapat pujian atas keberhasilan mencegah terjadinya pembunuhan massal. Nama Beltsazar tak disebut karena laki-laki itu melarang Inspektur Boris mengatakan apa-apa.
Pukul empat dini hari, Beltsazar terbangun dengan mendapati telepon genggamnya menerima email dari pengirim yang tak dikenal. Ia tercenung membaca isi email.
Di sebuah bukit yang jaraknya lima kilometer dari pusat kota. Saat itu matahari baru saja terbit. Beltsazar tiba di puncaknya dengan napas terengah.
“Halo, Beltsazar,” sapa seorang laki-laki yang berdiri di dekat sebuah patung malaikat tanpa sayap. Ia mengenakan topeng hitam yang hanya memperlihatkan area mata yang sekelam malam.
“Kau yang mengirimiku email. Siapa kau?”
“Kupikir kau tak perlu bertanya, karena aku yakin kau pasti sudah bisa menebak siapa aku.” Suara laki-laki bertopeng itu serak dan mencekam.
“Kau yang membunuh orang-orang tak berdosa itu. Yang mengatasnamakan para malaikat demi memenuhi obsesi sakit jiwamu.”
“Ow… Beltsazar… Beltsazar. Aku sungguh tersinggung kau mengataiku sakit jiwa. Aku ini adalah seorang maestro. Aku adalah pencipta teror yang akan dikenal dunia karena ketakutan yang kudatangkan atas manusia. Hanya orang jenius yang mampu melakukan itu semua bukan orang sakit jiwa.”
“Berhentilah terobsesi menjadi Lucifer. Kau bukan siapa-siapa yang hanya akan membusuk di penjara demi dosa-dosamu itu.”
“Ha ha ha. Aku tak pernah terobsesi. Karena aku adalah Helel sang pembawa teror. Dan kau tahu, tindakanmu menyelamatkan orang-orang itu adalah tindakan bodoh. Karena kesalahanmu itu, aku akan memberi teror yang lebih besar lagi untuk kota ini.”
“Aku adalah orang yang akan menghentikan segala kegilaanmu itu.”
“Kau tak akan pernah bisa menghentikanku. Sama seperti yang sudah aku lakukan sebelumnya. Ucapkan selamat tinggal, Beltsazar. Kita akan berjumpa lagi. Secepatnya.” Laki-laki bertopeng itu tiba-tiba melompat dari atas bukit. Beltsazar baru akan mengejarnya ketika sebuah ledakan menghancurkan patung malaikat tanpa sayap menjadi serpihan debu.
Beltsazar bangun dengan tertatih. Daya ledak bom di patung membuatnya terhempas cukup jauh. Laki-laki bertopeng itu sudah tak kelihatan lagi. Tapi Beltsazar yakin, mereka akan bertemu kembali. Dan saat itu terjadi, Beltsazar sendiri yang akan menangkap laki-laki yang menyebut dirinya Helel. The Shining Ones.